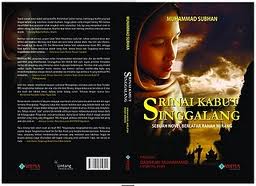 Rinai Kabut Singgalang (RKS) karya Muhammad Subhan terbit pada Januari 2011 menyemarakkan dunia sastra Indonesia. Novel ini seperti gabungan antara novel semibiografis dan novel islami, hanya saja menggunakan gaya bahasa klasik, seperti karya sastra Indonesia paruh pertama abad 20. Novel ini membawa ingatan saya pada gaya tutur roman Siti Nurbaya atau pun Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck; gaya bahasa yang mendayu-dayu seperti puisi dan cenderung menggunakan kalimat inversi—predikat mendahului subjek.
Rinai Kabut Singgalang (RKS) karya Muhammad Subhan terbit pada Januari 2011 menyemarakkan dunia sastra Indonesia. Novel ini seperti gabungan antara novel semibiografis dan novel islami, hanya saja menggunakan gaya bahasa klasik, seperti karya sastra Indonesia paruh pertama abad 20. Novel ini membawa ingatan saya pada gaya tutur roman Siti Nurbaya atau pun Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck; gaya bahasa yang mendayu-dayu seperti puisi dan cenderung menggunakan kalimat inversi—predikat mendahului subjek.
Muhammad Subhan secara tidak langsung telah memberi sinyal bahwa novelnya ini memang sangat terinpirasi—atau terobsesi?—dengan karya-karya Buya Hamka. Di awal buku, kita disuguhkan kutipan buku Hamka, “Seni tidak ada kalau cinta tidak ada. Apa sebabnya ada keindahan? Sebabnya ialah karena adanya cinta. Dengan cinta alam diciptakan. Tiap awal Quran dimulai dengan ‘Bismillahirrahmanirrahim’. Di atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah kunci rahasia cinta di alam ini. Timbulnya perasaan halus ialah karena cinta. Segala seni yang tinggi, syair, musik, lukisan, adalah laksana rumus untuk membuktikan adanya Yang Rahman dan Yang Rahim, Sumber Segala Cinta.” Selain itu, buku-buku Hamka berulang-ulang disebut oleh tokoh Fikri dan Yusuf di dalam cerita. Bahkan, judul novel Fikri yang best seller adalah Merantau ke Padang, sangat mirip dengan karangan Hamka, Merantau ke Deli. Kisah hidup Fikri pun mempunyai pertalian erat dengan romantisme Zainuddin dan Hayati.
Novel ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Fikri yang keturunan Aceh-Minang (Pasaman). Setelah ayahnya meninggal—tanggal 12 Juli 1995—Fikri pergi merantau ke Padang. Ibunya yang mulai sakit-sakitan tinggal bersama Annisa, adiknya. Sebelum ke Padang, Fikri terlebih dahulu pergi ke kampung ibunya dan bertemu dengan pamannya yang dipasung karena mengalami gangguan jiwa, Mak Safri. Dia cukup betah tinggal di kampung yang terletak di kaki Gunung Talamau itu, hingga kemudian ketidaksenangan sejumlah pemuda setempat membuatnya kembali pada misinya semula: Kuliah di IAIN. Sahabat barunya bernama Yusuf menghadiahinya tiga buah buku karangan Hamka, yaitu Merantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Ka’bah, dan Tenggelamnya kapal Van Der Wijck. Sesampai di Padang, Fikri terluka karena membantu seorang gadis yang dicopet. Gadis itu bernama Rahima, putri Bu Aisyah yang pernah satu bus dengannya dari Aceh dulu.
Atas bantuan Bu Aisyah, Fikri mendapat orang tua angkat di Teluk Bayur, yakni Pak Usman dan Bu Rohana. Antara Fikri dan Rahima talah tumbuh rasa cinta, namun tidak diungkapkan. Barulah di akhir tahun 2004, ketika tsunami menerjang Aceh, termasuk keluarga Fikri, Rahima berterus terang tentang perasaannya melalui sepucuk surat. Pada waktu itu dia hendak dijodohkan oleh kakaknya, Ningsih, yang tinggal di Jakarta. Fikri pergi ke Aceh sebagai relawan dan bertemu dengan Annisa yang sakarat.
Sekembalinya ke Padang, Fikri melamar Rahima melalui Yusuf yang telah meninggalkan Kajai karena batal menikah. Ningsih menolak, dan Bu Aisyah yang sakit-sakitan karena melihat pertengkaran anak-anaknya meninggal dunia. Rahima pun dibawa kakaknya ke Jakarta dan dinikahkan. Fikri yang patah hati kemudian mengarang novel berjudul Merantau ke Padang. Novel itu menjadi best seller, dicetak ulang, dan Fikri pun terkenal. Setelah kuliahnya selesai, dia pindah ke Bukittinggi untuk meneruskan karir kepengarangannya. Novel terbarunya Ode di Tanah Penantian kembali meledak di pasaran dan difilmkan.
Sementara itu, rumah tangga Rahima mengalami krisis dan berujung pada perceraian. Ketika Fikri ke Jakarta menghadiri pemutaran film Ode di Tanah Penantian Rahima melihatnya. Dia pun gundah gulana dan jatuh sakit. Fikri yang telah balik ke Bukittinggi mendapat surat dari Ningsih yang memohon maaf dan memintanya menengok Rahima. Fikri pun ke Jakarta dan membawa Rahima ke Padang. Namun, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan ketika mendarat di bandara. Ningsih berserta suami dan anak-anaknya tewas. Fikri yang luka parah meminta Yusuf membawanya ke sebuah rumah impiannya di Koto Baru, Padang Panjang. Sebelum meninggal, dia ‘mewasiatkan’ Yusuf agar menikahi Rahima.
Kisah dan gaya bercerita RKS telah mengembalikan kita pada khazanah sastra klasik yang penuh dengan resapan-resapan pelajaran kehidupan, walau ditingkahi duka cita berurai air mata dan adegan yang cenderung melodramatis. Kerinduan para pecinta sastra akan karya yang sedap dibaca dan langsung dapat dipetik hikmahnya, terobati dengan kehadiran novel yang segera dicetak ulang ini.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan sebuah karya sastra disukai pembaca, di antaranya adalah ketika karya tersebut dapat merepresentasikan diri pembaca dengan adanya kedekatan emosi dan mampunya karya tersebut menampilkan gagasan dan harapan terdalam dari diri pembaca. Kebanyakan orang sangat senang merefleksikan diri dengan hal yang diminatinya, termasuk atas karya sastra. Bila bukan karena adanya kesamaan nasib dengan tokoh yang dihidupkan di dalam cerita, biasanya hati pembaca tertambat pada jalinan kisah yang menyerupai hasrat dan impiannya.
RKS berhasil mengaduk-aduk tiga hal yang sangat potensial untuk merebut perhatian pembaca, yakni luka, cinta, dan cita-cita. Para pembaca yang berhati sehalus sutra akan terpiuh-piuh perasaannya membaca getirnya kehidupan Fikri. Kemalangan hidup Fikri begitu memilukan, sementara keberuntungannya yang dapat keluar dari kesulitan hidup dan meraih cita-cita terasa amat mengharukan. Motivasi Fikri yang begitu besar untuk kuliah dapat menggugah pembaca yang suka kisah-kisah inspiratif. Jalan cerita yang linier dan mudah dicerna dirangkai dengan gaya bahasa yang elok dan cenderung puitis membuat novel ini mudah dinikmati siapa pun.
Apabila dicermati, di balik semua kemalangan hidupnya yang mengundang simpati, sosok Fikri ternyata terlalu ‘sempurna’. Kecuali berasal dari keluarga miskin dan orang tua terbuang dari kaum, dia adalah pemuda yang gagah, berakhlak baik, taat dan punya ilmu agama, rajin, lemah lembut, berpikiran maju, serta pintar mengarang sehingga menjadi penulis terkenal. Apa yang dialami Fikri terkesan lempeng, begitu lurus tanpa banyak rintangan sehingga sosok Fikri menjadi begitu romantis. Kisah hidup Fikri setelah menjadi pengarang terkenal yang diundang ke mana-mana dan menginap di hotel mewah, serasa dongeng yang kelewat indah.
Konflik di dalam RKS lebih dominan berupa konflik emosional yang melibatkan relasi antartokoh. Di bagian awal sempat digambarkan konflik budaya (adat) yang melatari kehidupan orang tua Fikri, dan polah tingkah Fikri yang berbudi pekerti baik menunjukkan adatnya sebagai orang berbangsa. Konflik yang lebih komplet dan ruwet nyaris tidak kita temukan. Semuanya berjalan ‘lancar’ tanpa degresi. Barangkali ini dapat dimaklumi karena ‘obsesi Hamka’ tadi. Aneka kemalangan dan kematian yang jatuh mendera Fikri dan tokoh-tokoh di seputar kehidupannya semakin mempertajam konflik emosional di dalam cerita.
Pesona lain yang ditawarkan Rinai Kabut Singgalang adalah keindahan negeri yang menjadi latarnya, yakni Sumatra Barat. Ah, andai Gamawan Fauzi masih menjadi gubernur Sumatra Barat, tentu Bapak Yang Terhormat itu terpaksa menggigit lidah sendiri karena tidak hanya Andrea Hirata yang berhasil mempromosikan kampung halamannya Pulau Belitong lewat Laskar Pelangi, Muhammad Subhan pun mampu berbuat serupa dengan mempromosikan keindahan alam Ranah Minang melalui novelnya ini. Dan, jika instansi kepariwisataan Sumbar cukup kreatif, novel ini bisa juga mendongkrak popularitas Tour de Singkarak seandainya dijadikan suvenir.
Bagi orang Minang yang tinggal di rantau, RKS dapat menjadi pengobat rindu pada kampung halaman. Lewat perjalanan Fikri, kita ikut dibawa ke tempat-tempat eksotis, seperti Gunung Talamau, Danau Maninjau, Bukittinggi, Padang Panjang, Lembah Anai, Pantai Padang, dan tentu saja daerah antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Bagi orang Minang yang tinggal di Sumbar pun, novel ini tentu membanggakan karena memuat tempat-tempat indah yang menjadi ikon keistimewaan negri. Patut juga untuk dilagakkan pada orang luar daerah.
Selain tempat-tempat yang tak terlupakan, RKS juga membawa pembacanya untuk mengenang orang-orang besar dari Sumbar, seperti Buya Hamka yang rumah masa kecilnya disinggahi Fikri di Maninjau dan Bung Hatta sang tokoh proklamator yang rumah kelahirannya dijadikan lokasi peninggalan sejarah di Bukittinggi. Sebagai pembaca, kita seperti diingatkan bahwa ranah ini pernah menyumbangkan orang-orang besar bagi republik tercinta.
Tak hanya tokoh yang telah meninggal, RKS juga menghadirkan legenda hidup, yakni Taufiq Ismail, penyair gaek yang terkenal dengan sajak-sajak bersahaja penuh makna. Rumah Puisi di Aie Angek, Kabupaten Tanah Datar, tempat penulis RKS beraktivitas juga turut diceritakan. Pikiran iseng saya sempat bertanya-tanya, “Apakah Fikri sempat bertemu dengan Muhammad Subhan seperti Kerim Alakuºo”lu bersahabat dengan Orhan Pamuk sang pengarang Snow?”
Alur merupakan unsur yang sangat penting bagi prosa. Cerita yang sederhana dapat menjadi luar biasa ketika dikemas dengan rangkaian peristiwa yang menarik. RKS memakai alur maju yang konvensional. Alur seperti ini sangat berisiko membuat cerita jadi membosankan. Jalan keluar yang paling tepat adalah memberikan kejutan-kejutan sehingga pembaca tetap penasaran dan bersemangat membaca cerita hingga titik terakhir. Pengarang novel ini telah melakukannya dengan memberikan kejutan-kejutan di sejumlah bagian cerita. Kepenasaranan pembaca tentu terpelihara dengan menunggu-nunggu bagaimana akhir kisah cinta Fikri – Rahima.
Sebagai novel, RKS telah digarap dengan baik dan menunjukkan kerja keras pengarangnya. Susah membayangkan bisa merangkum konflik cerita dengan aneka peristiwa faktual, melengkapi dengan kearifan lokal, dan tetap ‘menjual’ pesona wisata. Muhammad Subhan patut diapresiasi sebagai sastrawan yang bersungguh-sungguh!
Namun demikian, ada beberapa hal yang cukup mengganggu ketika saya membaca novel ini. Pertama adalah munculnya peristiwa-peristiwa kebetulan, misalnya ketika Fikri tiba di Kota Padang dan menyaksikan pencopetan atas Rahima. Bagi saya adegan itu sangat tidak natural. Ada kebetulan-kebetulan lain yang mendukung keutuhan cerita namun terasa sekali aspek dramatisnya, seperti ketika Fikri bertemu Annisa yang sudah sekarat akibat tsunami dan Rahima melihat Fikri yang telah terkenal di Jakarta.
Masuknya Tragedi Tsunami Aceh 2004 juga terasa dipaksakan agar kegetiran hidup Fikri semakin tak terkatakan. Saya telah menghitung-hitung dan menemukan ada bagian kisah yang hilang—menyebabkan lubang pada alur—yakni rentang kepergian Fikri merantau ke Padang hingga peristiwa tsunami Aceh. Fikri pergi merantau tak lama setelah ayahnya meninggal (tahun 1995), sebelum ke Padang dia singgah di Kajai dan sempat tinggal sebentar. Akhir 1995 atau pada tahun 1996 dia tinggal di Padang dan pada saat itu Rahima masih duduk di madrasah aliyah. Cerita melompat ke tahun 2004, saat rasa cinta Rahima dan Fikri diungkap, artinya delapan tahun kemudian. Waktu delapan tahun tentu tidak sebentar. Namun tidak dijelaskan apa yang terjadi, apakah Fikri telah mulai kuliah dan bagaimana dengan Rahima?
Selain itu, keberuntungan Fikri yang mengarang dan menerbitkan novel hingga menjadi pengarang terkenal juga membuat saya bertanya-tanya, novel seperti apa yang dikarang Fikri sehingga bisa sehebat itu? Apakah tokoh Fikri sedikit terinspirasi dengan kesuksesan Habiburahman el Shirazy, Andrea Hirata, atau Ahmad Fuadi?
Namun sudahlah, namanya juga novel, bukan? Fiksi! Semoga dapat menjadi alternatif bacaan bagi para pelajar, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, pengusaha, penulis lain, wartawan, pejabat, atau koruptor. Setiap pencapaian pasti akan mendapat tempat. Salut untuk Muhammad Subhan!
Ragdi F. Daye (Sastrawan & anggota FLP , tinggal di Padang)
Dimuat di Haluan Minggu, 12 Juni 2011
